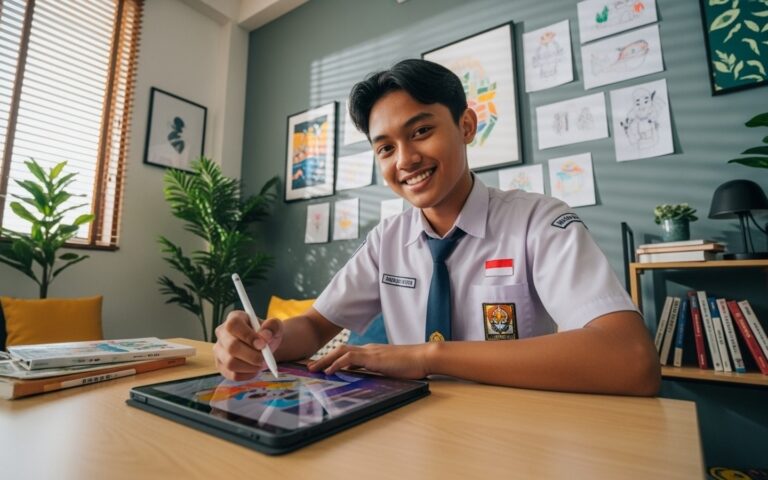Sains bukan hanya soal penemuan. Melalui literasi, kolaborasi, dan inovasi, Indonesia bisa berperan membangun perdamaian dan masa depan yang berkelanjutan.
Setiap kali dunia dihadapkan pada krisis, dari pandemi hingga perubahan iklim, sains selalu menjadi cahaya kecil yang menuntun arah. Namun di balik kemajuan teknologi yang menakjubkan, terselip keraguan publik, ketimpangan akses, dan hilangnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan.
Dunia memperingati World Science Day for Peace and Development pada setiap tanggal 10 November. Ini merupakan salah satu rangkaian dari keseluruhan International Week of Science and Peace yang selalu diselenggarakan pada tanggal 9 – 15 November, dan tema yang perayaan yang diangkat UNESCO pada tahun 2025 ini adalah “Trust, transformation, and tomorrow: The science we need for 2050” yang mengingatkan kita bahwa masa depan bergantung pada bagaimana kita membangun kepercayaan terhadap sains hari ini.
Pada Agustus 2023, United Nations General Assembly (UNGA) menetapkan periode 2024-2033 sebagai International Decade of Sciences for Sustainable Development (Dekade Internasional Ilmu Pengetahuan untuk Pembangunan Berkelanjutan). Dalam konteks ini, World Science Day for Peace and Development UNESCO 2025 akan menjadi kesempatan untuk merenungkan jenis ilmu pengetahuan, serta jenis hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dekade-dekade mendatang.
UNESCO menegaskan bahwa sains bukan hanya tentang penemuan, melainkan tentang kemanusiaan. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam memperkuat perdamaian karena ia mengajarkan dialog, kolaborasi, dan pemahaman lintas batas. Dunia riset bekerja dengan bahasa universal yang tidak mengenal agama, ras, atau politik, melainkan berlandaskan pada data, bukti, dan empati terhadap kebenaran.
Contohnya terlihat dalam kolaborasi ilmiah internasional selama pandemi COVID-19. Ribuan ilmuwan di seluruh dunia membuka data riset secara publik dan berbagi temuan dalam waktu nyata, menghasilkan pengembangan vaksin dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kolaborasi semacam itu menunjukkan bahwa sains mampu menjadi jembatan antarnegara, bahkan di tengah perbedaan politik dan budaya.
Namun, di Indonesia, sains masih sering dipandang eksklusif dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Budaya riset belum sepenuhnya tumbuh di masyarakat, dan hasil penelitian sering tidak sampai ke ruang publik. Jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu 395 peneliti per juta orang. Angka ini jauh di bawah rata-rata global, yaitu sekitar 1.368 peneliti per juta penduduk. Bahkan negara tetangga seperti Singapura memiliki lebih dari 7.000 peneliti per juta penduduk.
Hal ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi cerminan ekosistem sains yang belum sepenuhnya terhubung dan berkembang.
Selain itu, laporan Guidelines for Regulating Digital Platforms menyebutkan bahwa penyebaran disinformasi dan misinformasi, terutama di bidang kesehatan dan sains, menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik pada lembaga ilmiah dan akademik. Sementara itu, setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara itu, hanya 21% sampai 36% yang mampu mengenali hoaks. Ketika teori konspirasi dan informasi palsu menyebar lebih cepat daripada publikasi ilmiah, ruang dialog ilmiah pun menyempit. Padahal membangun kepercayaan publik terhadap sains sama pentingnya dengan melakukan riset itu sendiri.
Masa depan sains di Indonesia tidak bisa diserahkan pada segelintir akademisi. Membutuhkan ekosistem yang hidup, terbuka, dan manusiawi untuk dapat memajukan dan mengembangkan sains di Indonesia.
Ada beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan bersama:
- Memperkuat literasi sains sejak dini. Sains pada anak-anak usia dini dapat diartikan sebagai stimulus mereka untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, dan mengaitkan antar konsep maupun peristiwa.
- Memperluas kolaborasi lintas disiplin. Sains harus bersentuhan dengan seni, etika, ekonomi, dan kebijakan publik. Perubahan besar hanya mungkin terjadi ketika ilmu pengetahuan menjadi bagian dari kehidupan sosial, bukan sekadar urusan laboratorium. Inisiatif seperti Indonesia Research and Innovation Expo (Inari Expo) yang mempertemukan peneliti, pemerintah, dan pelaku industri adalah langkah positif yang patut diperluas.
- Mendukung riset yang berakar pada masalah nyata masyarakat. Indonesia menghadapi banyak tantangan, dari ketahanan pangan hingga krisis iklim, yang menuntut inovasi lokal. Ketika hasil riset membantu petani memprediksi cuaca atau masyarakat pesisir mengelola air bersih, sains menemukan maknanya yang sejati.
- Membangun kepercayaan publik terhadap sains melalui komunikasi yang jujur dan mudah dipahami. Para ilmuwan, pendidik, dan pembuat kebijakan perlu lebih aktif bercerita tentang riset mereka dengan bahasa yang hangat dan kontekstual. Pengetahuan tidak akan bermakna jika tidak bisa dipahami oleh mereka yang membutuhkannya.
UNESCO menekankan bahwa masa depan sains harus dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Tahun 2050 mungkin masih jauh, tetapi arah ke sana dimulai hari ini. Ketika sekolah-sekolah menumbuhkan rasa ingin tahu, ketika universitas membuka pintu bagi kolaborasi, dan ketika masyarakat percaya bahwa ilmu membawa kebaikan, maka sains benar-benar menjadi alat perdamaian.
Sains tidak bisa berjalan sendiri tanpa masyarakat yang memercayainya. Sains hanya dapat bermakna ketika digunakan untuk memperbaiki kehidupan, mengurangi penderitaan, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil.
World Science Day for Peace and Development mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar penemuan, melainkan jalan menuju perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kolaborasi, literasi sains, dan riset berbasis kemanusiaan, Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan terhadap sains menuju masa depan 2050.
Penulis: Dania Ciptadi
Editor: Astrid Prahitaningtyas
Artikel terkait: